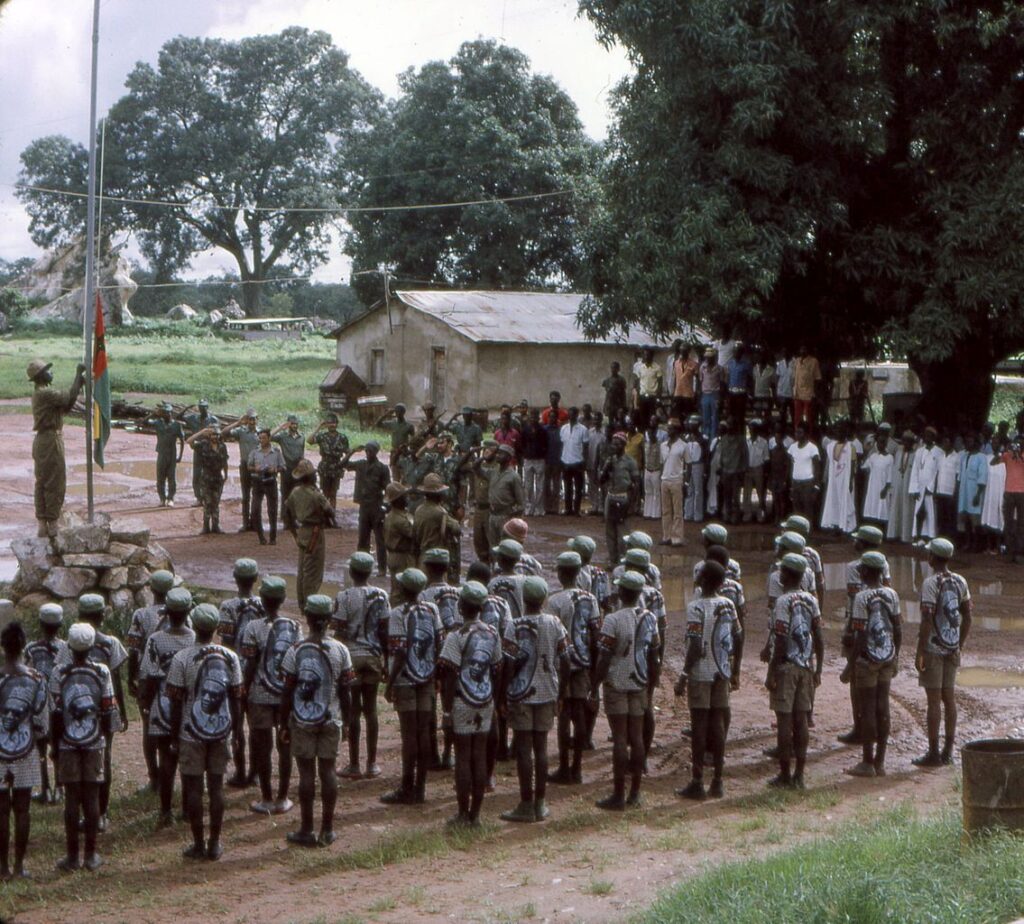marylandleather.com, 2 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88
Nauru, sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik dengan luas hanya 21 kilometer persegi, adalah salah satu negara terkecil di dunia. Meskipun kecil, sejarah kemerdekaannya adalah kisah epik tentang ketahanan, perjuangan, dan tekad rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri. Hari Kemerdekaan Nauru, yang diperingati setiap tanggal 31 Januari, bukan hanya merayakan kebebasan dari kolonialisme, tetapi juga mencerminkan perjalanan panjang melawan eksploitasi sumber daya, penjajahan, dan tantangan global. Artikel ini menggali secara mendalam sejarah kemerdekaan Nauru, dari masa pra-kolonial hingga kedaulatan penuh pada 31 Januari 1968, dengan fokus pada konteks historis, perjuangan rakyat, dan dampaknya terhadap identitas nasional. Berdasarkan sumber terpercaya seperti laporan National Today, artikel Koran Sulindo, dan analisis akademik, panduan ini menyajikan narasi yang rinci, profesional, dan jelas tentang perjalanan Nauru menuju kedaulatan.
Latar Belakang Geografis dan Budaya Nauru 
Nauru terletak di Pasifik Tengah, sekitar 42 kilometer di selatan garis khatulistiwa, menjadikannya salah satu pulau terpencil di dunia. Dengan populasi sekitar 10.000 jiwa pada tahun 2025, Nauru dihuni oleh 12 suku asli yang memiliki budaya dan bahasa sendiri, yaitu bahasa Nauru. Bendera nasional Nauru mencerminkan identitas ini: latar biru melambangkan Samudra Pasifik, garis emas menandakan garis khatulistiwa, dan bintang putih dengan 12 titik mewakili 12 suku asli, dengan warna putih yang juga melambangkan fosfat—sumber kekayaan utama pulau ini. Lagu kebangsaan, Nauru Bwiema, yang ditulis oleh Margaret Hendrie dan digubah oleh Laurence Henry Hicks pada 1962, menjadi simbol kebanggaan nasional yang menggambarkan cinta terhadap tanah air dan semangat persatuan.
Sebelum kedatangan penjajah Eropa, masyarakat Nauru hidup dalam sistem klan yang terorganisir, dengan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, dan perdagangan antar-pulau. Namun, kekayaan fosfat di pulau ini, yang ditemukan pada akhir abad ke-19, mengubah nasib Nauru, menarik perhatian kekuatan kolonial dan memicu eksploitasi yang berlangsung selama beberapa dekade.
Masa Kolonial: Eksploitasi dan Penjajahan
1. Kedatangan Eropa dan Kolonisasi Jerman (1888–1914) 
Sejarah kolonial Nauru dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Jerman mengklaim pulau ini sebagai bagian dari protektoratnya di Pasifik. Pada 1888, Nauru secara resmi dianeksasi oleh Kekaisaran Jerman setelah negosiasi dengan kepala suku setempat, yang sering kali tidak sepenuhnya memahami implikasi perjanjian tersebut. Jerman tertarik pada Nauru karena deposit fosfatnya yang sangat berharga untuk industri pertanian global, terutama sebagai bahan baku pupuk.
Selama periode ini, perusahaan Jerman seperti Pacific Phosphate Company mulai mengeksploitasi fosfat secara besar-besaran. Penambangan fosfat tidak hanya merusak lanskap pulau, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat adat. Tanah-tanah subur dihancurkan, dan penduduk lokal sering dipaksa bekerja di tambang dengan upah rendah. Meskipun ada resistensi sporadis dari masyarakat Nauru, kekuatan militer Jerman dan kurangnya persatuan antar-suku membuat perlawanan sulit dilakukan.
2. Mandat Liga Bangsa-Bangsa dan Administrasi Australia (1914–1942) 
Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, Nauru diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa melalui Perjanjian Versailles pada 1919. Pulau ini ditempatkan di bawah mandat bersama Inggris, Australia, dan Selandia Baru, dengan Australia sebagai pengelola utama. Sistem mandat ini seharusnya melindungi kepentingan penduduk asli, tetapi dalam praktiknya, penambangan fosfat terus berlanjut di bawah British Phosphate Commission (BPC), yang mengendalikan industri fosfat.
Penduduk Nauru hanya menerima royalti kecil dari keuntungan penambangan, sementara sebagian besar keuntungan mengalir ke Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Eksploitasi ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, dengan sekitar 80% permukaan pulau menjadi tidak subur akibat penambangan. Selain itu, penduduk lokal menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi, dengan akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan.
Pada periode ini, kesadaran nasional mulai muncul di kalangan elit Nauru yang terdidik. Tokoh seperti Timothy Detudamo, seorang kepala suku dan penerjemah, mulai mengadvokasi hak-hak penduduk asli dan menuntut royalti yang lebih adil. Namun, perubahan signifikan belum terjadi karena kekuatan kolonial yang dominan.
3. Pendudukan Jepang Selama Perang Dunia II (1942–1945)

Selama Perang Dunia II, Nauru diduduki oleh Jepang pada Agustus 1942. Pendudukan ini merupakan salah satu periode paling kelam dalam sejarah Nauru. Jepang menggunakan pulau ini sebagai pangkalan militer dan melanjutkan penambangan fosfat untuk keperluan perang. Namun, kondisi kehidupan penduduk lokal memburuk drastis.
Pada 1943, sekitar 1.200 warga Nauru—hampir dua pertiga populasi—dideportasi ke Truk (sekarang Laguna Chuuk) di Kepulauan Caroline untuk bekerja sebagai pekerja paksa. Deportasi ini menyebabkan penderitaan besar, dengan banyak warga Nauru yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan buruk. Dari 1.200 orang yang dideportasi, hanya sekitar 737 yang selamat dan kembali ke Nauru pada 1946 setelah Jepang menyerah.
Pendudukan Jepang meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat Nauru. Namun, pengalaman ini juga memperkuat rasa solidaritas dan semangat nasionalisme, karena penduduk Nauru menyadari perlunya kedaulatan untuk melindungi diri dari eksploitasi asing.
Perjuangan Menuju Kemerdekaan
1. Kembalinya Administrasi Australia dan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945–1968)
Setelah Perang Dunia II, Nauru kembali berada di bawah administrasi Australia, kali ini sebagai wilayah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 1947. Mandat perwalian ini, seperti mandat Liga Bangsa-Bangsa sebelumnya, dimaksudkan untuk mempersiapkan Nauru menuju pemerintahan sendiri. Namun, Australia terus memprioritaskan penambangan fosfat, dengan sedikit perhatian pada kesejahteraan penduduk lokal.
Pada 1950-an, gerakan menuju kemerdekaan mulai menguat, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hammer DeRoburt, yang kemudian menjadi presiden pertama Nauru. DeRoburt, seorang guru dan kepala suku yang terdidik di Australia, menjadi suara utama dalam menuntut hak atas tanah dan sumber daya fosfat. Ia bekerja sama
BACA JUGA: Panduan Lengkap Perawatan Kucing dari Bayi: Rinci, Profesional, dan Terorganisir
BACA JUGA: Sanctuary untuk Harimau: Konservasi dan Rehabilitasi
BACA JUGA: Planet-Planet di Tata Surya: Pertinjauan Lengkap